Bagian 3
Ki Jagatirta mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara orang di sebelahnya yang sudah cukup berumur telah beringsut dari duduknya sejengkal sambil bertanya, “Maaf Ki Gede, apakah telah ditunjuk seseorang untuk menjemput para tamu itu?”
“Sudah Ki Kamitua,” sahut ki Gede cepat, “Aku telah memerintahkan kepada Ki Wiyaga pagi tadi sebelum Matahari terbit untuk pergi ke dukuh Klangon menjemput para tamu kita.”
Ki Kamitua mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, “Ki Gede, para pengawal di Perdikan Matesih ini telah terpecah menjadi dua golongan. Sebagian tetap bersetia kepada Perdikan Matesih di bawah panji-panji kebesaran Mataram, sedangkan yang lainnya, terutama yang muda-muda, mereka lebih senang berangan-angan bersama para pengikut Trah Sekar Seda Lepen. Aku khawatir jika Ki Wiyaga sebagai pemimpin pengawal Perdikan Matesih lebih condong untuk mengikuti golongan yang terakhir.”
Terdengar orang-orang yang hadir di ruang dalam itu bergeremang satu dengan lainnya. Agaknya masing-masing mempunyai tanggapan yang berbeda.
“Ki Kamitua,” berkata Ki Gede kemudian sambil mengangkat tangan kanannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam sejenak, “Aku percaya dengan Ki Wiyaga. Dia telah menjadi pengawal perdikan Matesih sejak masih muda. Kedudukan pemimpin pengawal itu pun aku percayakan kepadanya setelah ayahnya mengundurkan diri karena usia tua. Jadi aku percaya kepada Ki Wiyaga sebagaimana dulu aku juga percaya kepada ayahnya.”
Sejenak mereka yang hadir di tempat itu terdiam. Masing-masing telah tenggelam dalam kenangan masa lalu yang tenang dan tentram.
“Perdikan Matesih adalah perdikan yang tenang dan damai,” berkata seorang yang rambutnya sudah putih semua dalam hati, “Hampir tidak ada gejolak sama sekali di tanah perdikan ini. Semua penghuninya hidup rukun, guyup dan saling membantu. Namun dengan kedatangan orang yang menyebut dirinya Trah Sekar Seda Lepen dan para pengikutnya itu, penghuni tanah Perdikan ini telah terpecah belah dan jauh dari yang disebut rukun dan damai.”
Pembicaraan itu terhenti sejenak ketika tiba-tiba saja terdengar pintu yang menghubungkan ruang dalam dengan dapur berderit. Sejenak kemudian dari pintu yang terbuka muncullah seorang gadis yang sedang beranjak dewasa sambil membawa nampan berisi minuman dan makanan.
Semua orang segera menundukkan wajahnya kecuali Ki Gede Matesih. Dipandanginya wajah anak perempuan satu-satunya itu dengan kening yang berkerut merut. Seraut wajah yang menginjak dewasa dengan segala kelebihannya dibanding dengan gadis-gadis sebayanya.
Ratri, nama gadis semata wayang Ki Gede itu segera berjongkok dan meletakkan minuman dan makanan di depan para tamu. Setelah semuanya selesai, Ratri pun kemudian segera mundur setapak untuk kemudian berdiri dan membalikkan badan. Sejenak kemudian gadis cantik dengan keindahan bentuk tubuh yang mulai beranjak dewasa itu pun telah hilang di balik pintu yang tertutup rapat.
Sepeninggal putrinya, tampak wajah Ki Gede menjadi muram, semuram langit yang sedang turun hujan.
Sambil menarik nafas dalam-dalam dan menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali, Ki Gede pun kemudian berdesis perlahan seolah-olah hanya ditujukan kepada dirinya sendiri, “Aku mungkin salah satu dari sekian banyak orang tua yang tidak mampu memberikan tuntunan yang baik kepada anaknya.”
Suara itu terdengar seperti sebuah keluh kesah atau penyesalan yang tiada taranya.
Orang-orang yang mendengar keluh kesah Ki Gede itu tidak ada yang berani mengangkat kepalanya atau pun membuka suara. Mereka tetap menundukkan kepala dalam-dalam menunggu apa yang akan disampaikan oleh Ki Gede.
“Ah, sudahlah,” berkata Ki Gede kemudian mencoba mencairkan suasana, “Semoga sebelum wayah tengange, para tamu kita telah hadir di rumah ini.”
Orang-orang itu pun mengangguk-anggukkan kepala mereka.
“Nah,” berkata Ki Gede selanjutnya, “Apakah masih ada yang ingin disampaikan?”
Namun sebelum salah satu dari orang-orang yang hadir itu membuka suara, tiba-tiba saja terdengar ketukan di pintu, pintu yang menghubungkan ruang dalam dengan pringgitan.
“Masuklah!” terdengar suara Ki Gede cukup lantang.
Sejenak kemudian terdengar pintu berderit dan seseorang telah muncul dari balik pintu.
“Ki Wiyaga?” hampir serentak mereka yang berada di ruang dalam itu telah berdesis.
Orang yang memasuki ruang dalam itu memang Ki Wiyaga. Namun tidak tampak luka di pundaknya. Bahkan bajunya tampak bersih serta memakai kain panjang yang bersih pula. Agaknya Ki Wiyaga sempat mampir ke rumah terlebih dahulu untuk berganti baju sebelum menghadap Ki Gede.
Setelah mengangguk terlebih dahulu kepada orang-orang yang hadir, terutama Ki Gede, Ki Wiyaga pun segera mengambil duduk di sebelah Ki Jagatirta.
Setelah menanyakan keselamatan Ki Wiyaga terlebih dahulu, barulah Ki Gede bertanya, “Ki Wiyaga, mengapa sepagi ini engkau sudah kembali?”
Sejenak Ki Wiyaga menarik nafas dalam-dalam untuk meredakan getaran di dalam dadanya. Jawabnya kemudian, “Maaf Ki Gede, aku belum sempat menjemput tamu-tamu kita di banjar Padukuhan Klangon.”
“Mengapa?” tiba-tiba dengan serta-merta Ki Jagatirta telah menyela. Namun begitu disadarinya Ki Gede telah berpaling ke arahnya, dengan cepat segera ditundukkan wajahnya.
“Ya, Ki Wiyaga,” sahut Ki Gede kemudian, “Apa sebenarnya yang telah terjadi?”
“Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga kemudian, “Telah terjadi suatu peristiwa diluar rencana kita.”
Ki Gede mengerutkan keningnya dalam-dalam. Katanya kemudian, “Jangan berputar-putar Ki Wiyaga. Ceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi.”
Ki Wiyaga sejenak ragu-ragu. Tanpa sadar, diedarkan pandangan matanya ke arah orang-orang yang hadir di ruangan itu.
Agaknya Ki Gede tanggap akan keragu-raguan kepala pengawal Perdikan Matesih itu. Maka katanya kemudian, “Ki Wiyaga, engkau berada di antara para bebahu perdikan Matesih yang dapat dipercaya.”
“Terima kasih ki Gede,” berkata Ki Wiyaga kemudian, “Kelima tamu kita itu ternyata dengan sengaja telah meloloskan diri dari banjar Padukuhan Klangon.”
“He?!” serentak mereka yang ada di ruangan itu terlonjak kaget, terutama Ki Gede. Sejenak wajahnya menjadi merah padam.
“Siapakah sebenarnya mereka itu?” geram Ki Gede, “Apakah mereka mencoba mempermainkan Ki Gede Matesih?”
“O, tidak, tidak Ki Gede,” sahut Ki Wiyaga cepat, “Sungguh mereka berlima itu orang-orang yang dapat dipercaya.”
“Dari mana Ki Wiyaga tahu?” sela Ki Kamitua.
Ki Wiyaga tersenyum. Sambil menyingkapkan baju di bagian pundak kirinya, Ki Wiyaga pun memperlihatkan bekas lukanya yang telah dibebat dengan secarik kain. Katanya kemudian, “Inilah buktinya. Salah satu dari mereka telah menolongku dari luka yang akan dapat membunuhku. Luka akibat goresan pisau belati yang sangat beracun.”
 Dalam pada itu, di ruang dalam padepokan, Raden Wirasena yang sedang duduk-duduk ditemani Kiai Damar Sasangka telah dikejutkan oleh suara siulan aneh yang terdengar sangat jelas dari ruang dalam itu.
Dalam pada itu, di ruang dalam padepokan, Raden Wirasena yang sedang duduk-duduk ditemani Kiai Damar Sasangka telah dikejutkan oleh suara siulan aneh yang terdengar sangat jelas dari ruang dalam itu.
“Begawan Cipta Hening?” desis Raden Wirasena. Namun terdengar nada suaranya sedikit ragu-ragu.
“He?!” kembali orang-orang itu terkejut. Bertanya Ki Gede kemudian, “Bagaimana itu bisa terjadi?”
Ki Wiyaga menarik nafas panjang sambil membetulkan bajunya kembali. Jawabnya kemudian, “Ceritanya panjang Ki Gede. Cerita itu dimulai ketika aku tanpa sengaja telah menemukan salah seorang pengawal perdikan Matesih, Lajuwit, sedang berusaha mengirim isyarat ke Perguruan Sapta Dhahana di lereng Gunung Tidar.”
Kemudian secara singkat Ki Wiyaga segera menceritakan kejadian di dekat gardu perondan itu serta pertemuannya dengan kelima orang yang mengaku dari Prambanan itu.
“Jadi engkau telah ditolong oleh mereka?” bertanya Ki Gede kemudian.
“Ya Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga, “Jika saja lukaku itu tidak segera diobati oleh orang yang bernama Ki Sedayu itu, mungkin aku sudah tidak dapat lagi berkumpul di tempat ini.”
“Ah!” beberapa orang justru telah berdesah. Sedangkan Ki Gede segera berkata, “Syukurlah agaknya Yang Maha Agung masih melindungi kita untuk menyelamatkan tanah perdikan ini dari segolongan orang yang tidak bertanggung jawab.”
Setiap orang yang ada di ruangan itu pun telah mengangguk-anggukkan kepala mereka.
“Bagaimana dengan Lajuwit?” tiba-tiba Ki Gede bertanya sambil memandang kearah Ki Wiyaga.
Sejenak Ki Wiyaga ragu-ragu. Bagaimanapun juga secara tidak sengaja dia telah ikut berperan dalam terjadinya rajapati, walaupun kejadian yang sebenarnya dia tidak begitu jelas.
“Mengapa engkau terlihat ragu-ragu Ki Wiyaga?” desak Ki Gede, “Katakanlah sejujurnya apa sebenarnya yang telah terjadi pada diri Lajuwit.”
“Maaf Ki Gede, jawab Ki Wiyaga kemudian setelah Menimbang-nimbang beberapa saat, “Lajuwit telah terbunuh oleh pisau beracunnya sendiri.”
“He?!” orang-orang yang berada di ruang itu pun kembali tersentak.
“Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?” hampir setiap mulut telah mengajukan pertanyaan yang serupa.
Namun Ki Wiyaga justru telah menggelengkan kepalanya. Jawabnya kemudian, “Aku tidak tahu, karena pengaruh racun itu begitu kuat sehingga aku telah jatuh pingsan. Namun sebelum aku benar-benar kehilangan kesadaranku, aku masih sempat mendengar suara benturan yang keras.”
“Mungkin Lajuwit telah menyerangmu sekali lagi dengan pisau belatinya di saat engkau lengah karena pengaruh racun itu,” berkata Ki Kamitua memberikan pendapatnya.
“Mungkin saja,” sahut Ki Gede, “Dan suara benturan keras yang engkau dengar itu adalah lontaran belati berikutnya yang mungkin telah dipatahkan oleh salah satu dari kelima orang itu.”
“Mungkin Ki Gede,” jawab Ki Wiyaga sambil mengangguk-angguk, “Kemungkinan itulah yang sebenarnya telah terjadi.”
“Berarti engkau telah berhutang nyawa dua kali kepada mereka, Ki Wiyaga,” kali ini Ki Jagatirta yang menyahut.
Ki Wiyaga tidak menjawab, hanya kepalanya saja yang terlihat terangguk-angguk.
Untuk beberapa saat ruangan itu pun justru telah menjadi hening.
Namun Ki Gede segera berusaha untuk menguasai keadaan. Maka katanya kemudian, “Semua itu mungkin sudah takdir dari Yang Maha Agung. Menurut pendapatku, Lajuwit telah memetik buah dari apa yang telah ditanamnya selama ini.”
Tampak semua orang mengangguk-anggukkan kepala mereka sambil menarik nafas dalam-dalam.
“Di manakah mayatnya sekarang?” bertanya Ki Gede kemudian.
“Mayat itu kami sembunyikan di bawah gardu,” jawab Ki Wiyaga, “Salah satu dari kelima orang itu telah menimbuninya dengan rumput-rumput kering agar tidak begitu tampak jika ada orang yang melewati gardu itu.”
“Baiklah,” berkata Ki Gede sambil memandang ke arah Ki Jagatirta, “Ki Jagatirta, bawalah beberapa orang yang dapat dipercaya bersama Ki Wiyaga nanti menjelang sirep uwong. Usahakan untuk tidak begitu menarik perhatian dan hanya kalangan kita saja yang mengetahui peristiwa ini.”
“Baik Ki Gede,” jawab Ki Jagatirta sambil menarik nafas panjang. Mengubur mayat di malam hari memang tidak menyenangkan, namun apa boleh buat. Perintah Ki Gede harus dilaksanakan.
“Nah, Ki Wiyaga,” berkata Ki Gede kemudian setelah sejenak mereka terdiam, “Mengapa engkau tadi mengatakan bahwa kelima orang itu dengan sengaja telah lolos dari banjar Padukuhan Klangon?”
Serentak semua mata segera tertuju ke arah Ki Wiyaga.
Menyadari semua orang sedang menunggu jawabannya, Ki Wiyaga pun segera beringsut setapak ke depan. Sambil membetulkan letak kain panjangnya terlebih dahulu, Ki Wiyaga pun kemudian bercerita tentang pengepungan para murid Padepokan Sapta Dhahana di banjar Padukuhan Klangon menjelang dini hari tadi. Sebagaimana seperti yang telah disampaikan oleh Ki Sedayu.
“Gila!’ geram Ki Gede begitu Ki Wiyaga selesai bercerita, “Ternyata kita kalah cepat dengan mereka,” Ki Gede berhenti sejenak. Kemudian sambil berpaling ke arah Ki Jagatirta, Ki Gede bertanya, “Ki Jagatirta, apakah engkau tahu di mana Ki Jagabaya sekarang ini?”
Untuk sejenak Ki Jagatirta memandang para bebahu lainnya untuk meminta pertimbangan. Namun semua bebahu yang hadir disitu telah menggelengkan kepala mereka. Maka jawab Ki Jagatirta kemudian, “Maaf Ki Gede, kami tidak tahu keberadaan Ki Jagabaya beberapa hari ini. Menurut keterangan yang aku peroleh, Ki Jagabaya sering terlihat berkunjung ke rumah yang ditempati Raden Surengpati dan pengikutnya.”
Kembali terdengar Ki Gede menggeram. Wajahnya terlihat sangat keruh. Berkata Ki Gede kemudian, “Kalian semua berhati-hatilah jika berbicara dengan Ki Jagabaya Perdikan Matesih. Aku melihat gelagat yang mencurigakan dari Ki Jagabaya,” Ki Gede berhenti sejenak.
Lanjutnya kemudian, “Lain halnya dengan Padukuhan Klangon, kalian dapat mempercayai Ki Jagabaya dukuh Klangon, namun jangan sekali-kali berbicara dengan Ki Dukuh Klangon. Dia telah terpengaruh dengan Raden Surengpati, sehingga Ki Dukuh Klangon sore tadi telah mengerahkan para pengawalnya untuk berjaga-jaga di banjar.”
“Untunglah kelima orang dari Prambanan itu mampu lolos dari pengamatan mereka,” sahut Ki Kamitua.
“Benar Ki Kamitua,” berkata Ki Wiyaga menanggapi kata-kata Ki Kamitua, “Dan yang lebih untung lagi, mereka berlima ternyata juga terhindar dari kepungan para murid gunung Tidar.”
“Itu menunjukkan bahwa mereka bukan segolongan orang-orang kebanyakan,” sahut Ki Gede dengan nada suara yang yakin dan mantap.
Para bebahu yang hadir di dalam ruangan itu pun tampak mengangguk-anggukkan kepala mereka.
“Nah, sekarang,” berkata Ki Gede selanjutnya, “Bagaimana cara kita untuk menghubungi mereka?”
Kembali semua mata tertuju ke arah Ki Wiyaga. Mereka berharap kepala pengawal perdikan Matesih itu dapat memberikan jawabannya.
Namun alangkah kecewanya para bebahu perdikan Matesih itu, terutama Ki Gede. Mereka melihat Ki Wiyaga justru telah menggelengkan kepalanya.
“Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, Ki Gede?” bertanya seorang yang rambutnya sudah putih semua.
Sejenak Ki Gede menarik nafas panjang. Ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata Ki Wiyaga, Ki Wiyaga pun segera tanggap. Maka katanya kemudian, “Ki Jagawana, kelima orang itu sudah berjanji akan menghadap Ki Gede, hanya waktunya saja yang belum pasti, sebab mereka masih mempunyai sebuah urusan untuk segera diselesaikan.”
“Urusan apa itu?” hampir bersamaan pertanyaan itu terdengar di ruangan itu.
Ki Wiyaga menggeleng. Jawabnya kemudian, “Aku tidak tahu dan aku tidak berani menanyakannya.”
Untuk beberapa saat suasana menjadi sunyi kembali. Masing-masing sedang tenggelam dalam angan-angan tentang permasalahan yang sedang dihadapi Perdikan Matesih.
“Nah, aku kira sudah cukup pembicaraan kita kali ini,” berkata Ki Gede kemudian memecah kesunyian, “Kalian dapat kembali ke tempat kerja masing-masing. Aku akan nganglang bersama Ki Wiyaga.”
Kemudian sambil berpaling ke arah kepala pengawal itu, Ki Gede pun telah menjatuhkan perintah, “Siagakan beberapa pengawal yang dapat dipercaya. Kita akan mengelilingi Tanah Perdikan Matesih ini untuk memberi kesan kepada para pengikut Trah Sekar Seda Lepen bahwa Perdikan Matesih masih ada dan akan tetap ada selama pemerintahan Mataram masih berdiri tegak.”
Demikianlah, perintah Ki Gede itu merupakan suatu perintah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sejenak kemudian pertemuan para bebahu itu pun telah selesai dan mereka segera kembali ke tempat tugas masing-masing.
Dalam pada itu, Ki Jayaraga dan Ki Bango Lamatan serta Glagah Putih yang mendapat tugas menyelidiki keberadaan Perguruan Sapta Dhahana dari lereng sebelah barat telah mendapat pesan dari Ki Rangga untuk mengamat-amati kediaman Ki Gede Matesih. Tanpa menarik perhatian mereka berjalan di antara ramainya lalu-lalang para pejalan kaki serta pedati-pedati yang sarat mengangkut hasil bumi. Sesekali mereka juga berpapasan dengan orang-orang yang berkuda.
“Guru, mengapa sejauh ini kita tidak melihat para pengawal Perdikan Matesih sedang meronda?” bertanya Glagah Putih yang berjalan di samping gurunya. Sementara beberapa langkah di belakang mereka, tampak Ki Bango Lamatan berjalan sambil menundukkan kepalanya.
“Entahlah Glagah Putih,” jawab gurunya, “Mungkin mereka merasa Perdikan ini sudah begitu aman, terutama di siang hari.”
“Kejahatan tidak mengenal waktu,” tanpa sadar Glagah Putih berdesis perlahan seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri.
“Engkau benar Glagah Putih,” sahut Gurunya, “Memang kejahatan tidak mengenal waktu dan tempat, akan tetapi lebih tepatnya, kejahatan pun memperhitungkan tempat dan waktu, karena seseorang yang akan melakukan sebuah tindak kejahatan juga mempunyai perhitungan-perhitungan.”
Glagah Putih mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar keterangan gurunya itu. Tanpa sadar dia kemudian berpaling ke belakang. Tampak Ki Bango Lamatan sedang berjalan sambil menundukkan kepalanya.
“Orang itu telah mengalami perubahan yang luar biasa dalam dirinya,” berkata Glagah Putih dalam hati sambil kembali memandang ke depan, “Aku masih ingat peristiwa di tepian kali Opak. Ki Bango Lamatan saat itu berada di pihak Panembahan Cahya Warastra dan sekarang tiba-tiba telah menjadi orang kepercayaan Pangeran Pati,” angan-angan Glagah Putih berhenti sejenak. Kemudian sambil tersenyum sekilas dia melanjutkan angan-angannya, “Semua itu berkat jasa Kanjeng Sunan.”
Tanpa terasa langkah mereka telah mendekati regol halaman rumah Ki Gede Matesih.
Ketiga orang itu pun kemudian berjalan sebagaimana orang-orang yang lain. Namun ketika mereka lewat tepat di depan regol, Glagah Putih telah menyempatkan diri untuk berpaling sekilas.
Tampak kening Glagah Putih berkerut. Apa yang dilihatnya hanya sekilas itu ternyata sangat berkesan. Diujung tangga pendapa dia sempat melihat seorang gadis cantik yang sedang beranjak dewasa tampak sedang bercakap-cakap dengan seseorang.
“Ratri,” tanpa sadar bibir Glagah Putih menyebut sebuah nama.
Ki Jayaraga yang berjalan di sampingnya terkejut. Sambil berpaling dia bertanya, “Siapa Glagah Putih?”
“O,” Glagah Putih tergagap. Setelah menarik nafas panjang barulah Glagah Putih menjawab, “Guru, aku tadi melihat seorang gadis yang sedang beranjak dewasa di tangga pendapa kediaman Ki Gede. Mungkin itu Ratri, putri satu-satunya Ki Gede Matesih.”
Ki Jayaraga mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, “Mungkin Glagah Putih. Gadis yang telah terpikat oleh seorang pria dewasa, yang mengaku sebagai Trah Sekar Seda Lepen.”
“Tentu Ratri telah terbuai oleh angan-angan dan janji-janji dari Raden Surengpati,” sahut Glagah Putih, “Jika perjuangan Trah Sekar Seda Lepen itu berhasil, dia akan ikut menikmati hasilnya. Hidup di kalangan istana, berlimpah ruah dengan harta benda, serta disuyuti dan dihormati oleh kawula seluruh negeri.”
“Ah,” Ki Jayaraga tertawa pendek mendengar ucapan Glagah Putih. Bahkan Ki Bango Lamatan yang berjalan beberapa langkah di belakang mereka pun ikut tersenyum.
Tanpa terasa langkah mereka telah semakin jauh dari regol halaman Ki Gede. Ketika mereka kemudian menjumpai sebuah jalan simpang, tiba-tiba Glagah Putih telah menghentikan langkahnya.
“Ada apa Glagah Putih?” bertanya Ki Jayaraga yang juga ikut berhenti. Sementara Ki Bango Lamatan yang berjalan beberapa langkah di belakang mereka telah memperlambat langkahnya.
“Guru, kita mengambil jalan ke kanan,” jawab Glagah Putih kemudian.
“Glagah Putih, jalan menuju ke Gunung Tidar adalah lurus ke depan,” tiba-tiba Ki Bango Lamatan yang telah ikut berhenti menyahut.
“Ki Bango Lamatan benar,” berkata Ki Jayaraga ikut menimpali, “Sebaiknya kita mengambil jalan lurus.”
Sejenak Glagah Putih ragu-ragu. Namun entah mengapa, seraut wajah cantik gadis putri ki Gede Matesih itu tidak mau hilang dari benaknya, walaupun beberapa saat tadi dia hanya melihatnya sekilas.
Setelah menarik nafas dalam-dalam, barulah Glagah Putih mengutarakan kegelisahannya.
“Guru,” berkata Glagah Putih kemudian, “Entah mengapa begitu melihat putri ki Gede tadi, rasa-rasanya aku telah mengkhawatirkan keselamatannya.”
Kedua orang tua itu sejenak saling pandang. Mereka segera menyadari, Glagah Putih agaknya telah tertarik dengan putri Matesih itu, apapun alasannya.
“Glagah Putih,” berkata Ki Jayaraga kemudian setelah melihat Ki Bango Lamatan yang tersenyum dan mengangguk-angguk, “Engkau tertarik pada putri Ki Gede itu memang sudah sewajarnya. Engkau masih muda dan putri Matesih itu pun seorang gadis yang sedang mekar-mekarnya. Namun sejauh manakah ketertarikanmu itu yang harus dipertanyakan.”
“Ah,” Glagah Putih berdesah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rona merah segera saja menghiasi wajahnya, namun dengan cepat segera saja Glagah Putih berusaha menghilangkan kesan itu dari wajahnya. Katanya kemudian, “Guru, aku menyadari bahwa aku adalah laki-laki yang sudah beristri. Aku hanya memikirkan bagaimana nasib putri Matesih itu jika dia benar-benar terjebak dalam jeratan orang yang mengaku Trah Sekar Seda Lepen itu.”
Untuk beberapa saat kedua orang tua itu justru telah terdiam. Memang akan saat mengenaskan nasib putri Matesih yang masih hijau itu jika dia sampai terperangkap jebakan Raden Mas Harya Surengpati.
“Ah, sudahlah,” akhirnya Ki Jayaraga berkata memecah kesunyian setelah sejenak mereka terdiam, “Kita hanya bisa mendoakan masa depan yang baik bagi putri Ki Gede itu.”
Ki Bango Lamatan mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar ucapan Ki Jayaraga, namun Glagah Putih justru mengerutkan keningnya dalam-dalam.
Ki Jayaraga yang melihat muridnya termenung telah menarik nafas panjang. Tanyanya kemudian, “Ada apa lagi Glagah Putih?”
“Maafkan aku Guru dan juga Ki Bango Lamatan,” jawab Glagah Putih kemudian, “Marilah kita bicarakan dengan sungguh-sungguh permasalahan ini”
Selesai berkata demikian Glagah Putih segera mempersilahkan kedua orang tua itu untuk berjalan menepi dan duduk di bawah sebatang pohon peneduh yang tumbuh di kanan jalan.
Setelah ketiganya menempatkan diri duduk di bawah bayangan pohon yang teduh itu, barulah Glagah Putih meneruskan kata-katanya, “Guru, aku mempunyai perhitungan bahwa saat ini Ki Wiyaga tentu telah melaporkan kejadian pagi tadi kepada Ki Gede Matesih.”
Serentak bagaikan telah berjanji, kedua orang tua itu mendongakkan wajahnya ke langit.
“Sudah hampir wayah tengange,” desis Ki Jayaraga
“Ya Ki Jayaraga,” sahut Ki Bango Lamatan, “Tentu Ki Gede sudah mendapat laporan dari Ki Wiyaga.’
“Nah Glagah Putih,” berkata Ki Jayaraga selanjutnya, “Apa hubungannya dengan Ratri, putri Ki Gede?”
“Guru,” jawab Glagah Putih kemudian. Tampak wajahnya bersungguh-sungguh sehingga kedua orang itu pun telah menaruh perhatian sepenuhnya, “Aku mempunyai dugaan bahwa apa yang telah dilaporkan oleh Ki Wiyaga kepada Ki Gede sedikit banyak akan diketahui oleh Raden Surengpati.”
Kedua orang tua itu saling pandang sejenak. Ki Jayaraga lah yang menanggapi, “Bagaimana mungkin, Glagah Putih? Ki Wiyaga tentu tidak gegabah dalam memberikan laporannya.”
“Benar, guru,” sahut Glagah Putih cepat, “Akan tetapi bagaimana dengan keluarga Ki Gede sendiri? Apakah tidak menutup kemungkinan Ratri mendengar walaupun hanya sekilas-sekilas dan kemudian menyampaikannya kepada Raden Surengpati.”
Kini kedua orang tua itu termenung. Memang hal itu sangat mungkin terjadi.
“Jadi apa rencanamu sekarang Glagah Putih?’ bertanya Ki Bango Lamatan kemudian.
Sejenak Glagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun baru saja Glagah Putih akan menjawab pertanyaan Ki Bango Lamatan, tiba-tiba dari kejauhan Glagah Putih melihat seseorang mendatangi tempat itu.
“Penjual dawet serabi,” desis Glagah Putih kemudian. Serentak kedua orang tua itu pun mengikuti arah pandang Glagah Putih.
“Apakah engkau haus Glagah Putih?” bertanya Ki Jayaraga kemudian sambil tersenyum.
Glagah Putih tidak segera menjawab. Pandangan matanya justru mengarah kepada Ki Bango Lamatan.
Ki Bango Lamatan pun lantas tertawa pendek. Katanya kemudian, “Alangkah segarnya minum dawet serabi di siang hari yang terik seperti ini.”
Ki Jayaraga dan Glagah Putih pun akhirnya ikut tertawa.
Demikianlah sejenak kemudian mereka bertiga telah memanggil penjual dawet serabi yang lewat di depan mereka.
Penjual dawet serabi itu pun segera berhenti dan menurunkan dagangannya. Dengan cekatan dilayaninya para pembelinya itu satu persatu.
“Ki Sanak,” berkata Glagah Putih kemudian setelah dia menyelesaikan minumnya lebih cepat dari kedua orang tua itu, “Kelihatannya mangkukku ini lebih kecil dibanding dengan mangkuk yang lainnya.”
“Ah,” penjual dawet itu tertawa, “Apakah engkau bermaksud menambah lagi, anak muda?”
Glagah Putih pun mengangguk sambil tertawa. Sementara Ki Jayaraga sambil menyenduk minumannya telah berkata kepada Glagah Putih, “Lain kali engkau membawa wadah sendiri saja, tempayan atau genthong barangkali.”
Yang mendengar kelakar Ki Jayaraga itu pun telah tertawa.
“Ki Sanak,” tiba-tiba penjual dawet itu berkata sambil memandang satu-persatu pembelinya, “Rasa-rasanya aku belum pernah melihat kalian. Dari manakah Ki Sanak semua ini?”
Sejenak mereka bertiga saling berpandangan. Ki Jayaraga lah yang akhirnya menjawab sambil mengembalikan mangkuknya yang telah kosong.
“Kami berasal dari Sangkal Putung,” jawab Ki Jayaraga sekenanya, “Dan kami sedang menuju ke Padukuhan Paran-paran.”
Penjual dawet ini mengerutkan keningnya. Tanyanya kemudian, “Di manakah letak Padukuhan Paran-paran itu Ki Sanak?”
Ki Jayaraga tersenyum. Jawabnya kemudian, “Padukuhan Paran-paran terletak di antara lembah Gunung Sindara dan Sumbing.”
“O,” penjual dawet itu tampak mengangguk-anggukkan kepalanya walaupun sebenarnya dia tidak mengetahui dengan pasti letak padukuhan itu.
“Terima Kasih Ki Sanak,” berkata penjual dawet itu kemudian ketika Ki Jayaraga membayar harga empat mangkuk dawet serabi, “Semoga perjalanan kalian menyenangkan.”
“Terima kasih,” jawab mereka bertiga hampir bersamaan.
“Semoga sekembalinya kami dari Paran-paran, kita dapat berjumpa kembali,” tambah Glagah Putih.
“O, tentu, tentu ki Sanak,” jawab penjual dawet itu sambil mengangkat pikulannya dan kemudian menaruh di pundaknya, “Hampir setiap hari aku melewati jalan ini.”
“Tapi engkau jangan lupa membawa tempayan,” sahut Ki Jayaraga sambil menggamit Glagah Putih yang segera saja disambut dengan gelak tawa.
Demikianlah setelah penjual dawet serabi itu pergi, Glagah Putih pun segera menyampaikan rencananya.
“Guru,” berkata Glagah kemudian, “Sebaiknya perjalanan kita ke Gunung Tidar kita tunda sebentar. Siang ini sampai nanti menjelang sore kita coba untuk mengamati kediaman Ki Gede. Barangkali putri Ki Gede akan keluar menemui Raden Surengpati untuk menyampaikan berita yang telah dibawa oleh Ki Wiyaga.”
Ki Jayaraga mengerutkan keningnya sambil memandang Ki Bango Lamatan. Agaknya guru Glagah Putih itu meminta pertimbangan untuk menyetujui rencana Glagah Putih.
Untuk sejenak Ki Bango Lamatan termenung. Namun tiba-tiba saja Ki Bango Lamatan berdesis perlahan, “Bagaimana jika yang terjadi justru sebaliknya? Raden Surengpati itu yang menemui Ratri di kediaman Ki Gede?”
Sekarang giliran Glagah Putih yang tertegun. Kemungkinan itu memang ada, namun menilik tanggapan Ki Gede yang tidak menginginkan putri satu-satunya itu menjalin hubungan dengan orang yang mengaku sebagai Trah Sekar Seda Lepen itu, kemungkinannya sangat kecil jika Ki Gede mengijinkan Raden Surengpati menemui putrinya.
Maka jawab Glagah Putih kemudian, “Kemungkinan itu sangat kecil, Ki Bango Lamatan. Aku justru cenderung hubungan mereka berdua itu masih sebatas sembunyi-sembunyi. Aku yakin mereka berdua belum berani berterus terang justru karena Ki Gede telah memperlihatkan sambutan yang kurang ramah atas kehadiran para pengikut Trah Sekar Seda Lepen itu di perdikan Matesih.”
“Engkau benar Glagah Putih,” berkata ki Jayaraga kemudian setelah sejenak berpikir, “Memang sebaiknya kita mengamati kediaman Ki Gede siang ini sampai sore nanti. Semoga apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi.”
Demikianlah sejenak kemudian ketiga orang itu segera meneruskan perjalanan. Mereka mengambil jalan yang berbelok ke kanan, jalan yang terlihat lebih kecil dari jalan sebelumnya.
“Agaknya jalan ini sangat jarang dilewati orang,” berkata Ki Jayaraga sambil mengayunkan langkahnya.
“Kelihatannya memang demikian, Ki,” sahut Ki Bango Lamatan sambil mengamat-amati pohon-pohon perdu liar yang tumbuh di sepanjang jalan, “Jalan ini sepertinya sebuah jalan pintas.”
“Aku juga mengira demikian,” kembali Ki Jayaraga berkata sambil ikut mengamati tanah pategalan yang kelihatannya sudah tidak terurus.
Sejenak kemudian jalan yang mereka lewati itu semakin lama menjadi semakin menyempit dan hanya tinggal jalan setapak saja yang terlihat menjelujur di antara rumput-rumput dan ilalang yang tumbuh liar di sana sini.
Selagi mereka berjalan sambil merenungi semak belukar yang semakin lebat, tiba-tiba saja pendengaran mereka yang tajam lamat-lamat telah mendengar langkah seseorang yang terdengar sangat tergesa-gesa dari arah kanan jalan. Memang masih cukup jauh, namun suara langkah itu begitu jelas terdengar di antara suara daun-daun yang tersibak dan ranting-ranting kecil yang berpatahan.
Untuk beberapa saat ketiga orang itu tidak tahu harus berbuat apa untuk menyikapi suara langkah yang terdengar semakin dekat itu. Namun ketika Ki Jayaraga kemudian menganggukkan kepalanya, serentak mereka bertiga pun segera bersembunyi di balik perdu-perdu yang banyak berserakan di tempat itu.
Sambil menahan nafas, mereka bertiga mencoba mengintip dari sela-sela dedaunan untuk melihat siapakah yang akan muncul dari pategalan di kanan jalan yang sudah tak terurus lagi itu.
Semakin lama suara langkah itu terdengar semakin keras. Sejenak kemudian dari balik sebatang pohon sawo kecik, muncul seraut wajah yang sangat dikenal oleh Glagah Putih.
“Ratri?” desis Glagah Putih dengan suara yang bergetar.
Kedua orang tua itu terkejut mendengar desis Glagah Putih sehingga telah berpaling ke arahnya.
“O, jadi itukah Ratri? Pantas!” bisik Ki Bango Lamatan sambil mengangguk-anggukkan kepalanya.
“Maksud Ki Bango Lamatan?” tanya Glagah Putih sambil berpaling.
Ki Bango Lamatan berpaling sekilas sambil tersenyum. Jawabnya kemudian, “Gadis yang bernama Ratri itu sangat cantik. Tentu banyak laki-laki yang ingin menyuntingnya.”
“Termasuk Ki Bango Lamatan barangkali,” sahut Ki Jayaraga
“Ah,” Ki Bango Lamatan hampir saja tidak dapat menahan tawanya, namun yang menjadi merah mukanya justru Glagah Putih.
“Lihatlah,” berkata Ki Jayaraga kemudian mengalihkan pembicaraan, “Putri Ki Gede itu memotong jalan dan memasuki pategalan di sebelah kiri jalan.”
“Kita ikuti,” sahut Glagah Putih cepat sambil berdiri dan kemudian melangkah menuju ke tempat putri Matesih itu menghilang.
Kedua orang tua itu sejenak saling berpandangan. Sambil menahan senyum akhirnya kedua orang tua itu pun berdiri dan melangkah mengikuti Glagah Putih.
Bukanlah sebuah pekerjaan yang sulit bagi ketiga orang itu untuk mengikuti jejak Ratri. Putri Ki Gede Matesih itu hanyalah seorang gadis kebanyakan yang tidak pernah diperkenalkan pada olah kanuragan sejak kecil.
Semakin lama ketiga orang itu semakin jauh memasuki pategalan yang sudah berubah menjadi seperti hutan kecil itu. Setelah melalui jalan setapak yang nyaris tak terlihat dan kemudian menurun, terlihat sebuah parit yang airnya mengalir bening.
“Parit ini mungkin digunakan sebagai pengairan ketika pategalan-pategalan ini masih digarap,” berkata Ki Jayaraga dalam hati sambil meloncati batang pohon yang tumbang karena lapuk dimakan usia.
Beberapa saat kemudian ketiga orang itu melihat Ratri telah berhenti di sepetak tanah yang ditumbuhi rumput. Di tanah sepetak itu kelihatannya dulu pernah didirikan sebuah gubuk untuk tempat beristirahat.
Sejenak Ratri terlihat masih berdiri termangu-mangu. Tampaknya dia sedang menunggu seseorang. Dengan raut wajah yang terlihat gelisah dia kemudian duduk di atas batu yang menjorok di sebelah parit yang airnya mengalir dengan bening.
Dalam pada itu di salah satu jalan di sebelah barat perdikan Matesih, tampak dua orang penunggang kuda, Eyang guru dan Raden Surengpati sedang memacu kudanya dengan sedikit kencang.
“Eyang guru,” berkata Raden Surengpati, “Di depan ada simpang tiga. Sebelum kita meneruskan perjalanan melalui jalan yang membelok ke kiri, ijinkan aku untuk menemui Ratri terlebih dahulu.”
“Raden,” jawab Eyang guru, “Apakah pertemuan itu dapat ditunda? Kita sebaiknya sampai di Tidar sebelum Matahari tergelincir jauh ke barat. Banyak hal yang harus kita bicarakan sehubungan dengan kedatangan Ki Rangga Agung Sedayu.”
“Aku paham Eyang guru,” jawab Raden Surengpati kemudian, “Namun sekarang ini adalah waktunya aku bertemu Ratri di tempat yang sudah kita sepakati. Mungkin Ratri membawa berita yang penting.”
Eyang guru menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, “Baiklah Raden. Kalau begitu aku menunggu saja di persimpangan. Aku tidak ingin mengganggu keasyikan kalian berdua.”
“Ah,” desah Raden Surengpati, “Ratri adalah gadis yang masih lugu. Dia selalu membawa kawan jika bertemu denganku.”
“He?!” terkejut Eyang guru mendengar keterangan Raden Surengpati.
Sambil berpaling sekilas, Eyang guru pun kemudian bertanya, “Apakah teman Ratri itu dapat dipercaya?”
“Ya, Eyang guru,” jawab Raden Surengpati mantap, “Kawannya itu adalah pemomongnya sejak kecil, jadi sudah dianggap seperti biyungnya sendiri. Apalagi sejak Nyi Gede meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, pemomongnya itu seolah-olah telah dianggap sebagai pengganti biyungnya.”
Eyang guru menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-angguk. Tak terasa derap langkah kaki-kaki kuda mereka telah mendekati simpang tiga.
“Aku akan menunggu di sini,” berkata Eyang guru kemudian sambil meloncat turun dan kemudian menambatkan kudanya pada sebatang pohon di pinggir jalan. Sementara Raden Surengpati masih belum turun dari kudanya.
“Apakah Raden akan berkuda?” bertanya Eyang guru sambil mengambil duduk di bawah sebatang pohon besar yang akar-akarnya tampak menonjol keluar.
Sejenak Raden Surengpati termenung. Namun akhirnya dia pun menjawab, “Aku akan berkuda saja Eyang guru. Tempatnya memang agak jauh dari sini.”
“Pergilah!” berkata Eyang guru sambil merebahkan dirinya bersandaran pada batang pohon itu.
“Terima kasih Eyang guru,” jawab Raden Surengpati kemudian, “Aku pergi dulu.”
Tanpa menunggu lagi, Raden Surengpati pun kemudian segera menghentak perut kudanya agar berlari maju.
Jarak antara simpang tiga dengan tempat yang biasa dijadikan pertemuan Raden Surengpati dengan Ratri memang cukup jauh. Setelah melalui jalan yang menurun, barulah Raden Surengpati membelokkan kudanya menyusuri jalan setapak memasuki sebuah pategalan.
Ketika jalan setapak itu telah menghilang tertutup rumput-rumput liar dan ilalang yang tumbuh rapat berjajar-jajar, Raden Surengpati pun segera menghentikan kudanya dan meloncat turun.
Sejenak Raden Surengpati menarik nafas panjang untuk memenuhi rongga dadanya dengan udara segar siang hari itu. Entah mengapa setiap akan berjumpa dengan Ratri, jantungnya selalu berdebar. Sebenarnyalah bagi Raden Surengpati bukan sekali ini saja dia berhubungan dengan perempuan, namun terhadap Ratri, dia mempunyai tujuan tersendiri.
“Ratri harus bisa membujuk dan meyakinkan ayahnya bahwa perjuangan Trah Sekar Seda Lepen ini memerlukan dukungan penuh dari perdikan Matesih,” berkata Raden Surengpati dalam hati sambil menambatkan tali kekang kudanya pada sebuah batang pohon, “Dengan direstuinya hubungan kami berdua, aku berharap Ki Gede akan legawa untuk melintirkan Perdikan Matesih ini kepadaku sehingga perdikan Matesih akan menjadi tumpuan utama dalam berjuang melawan Mataram.”
Sekali lagi Raden Surengpati menarik nafas panjang. Kemudian dengan langkah yang mantap dia mulai menuruni tanah yang agak miring menuju ke sebuah parit yang sudah tampak dari tempatnya berdiri.
Setelah sampai di tepi parit yang airnya mengalir bening, Raden Surengpati pun menyusuri parit itu mendekati tempat Ratri menunggu dari arah barat. Sementara Ki Jayaraga dan kawan-kawannya telah menempatkan diri di tempat yang agak jauh di sebelah timur dari tempat Ratri menunggu.
Dalam pada itu, Ratri yang sedang menunggu kedatangan Raden Surengpati itu menjadi semakin gelisah. Sesekali dia berdiri dari duduknya dan berjalan mondar-mandir. Namun ketika dirasakan kakinya menjadi penat, dia pun duduk kembali.
“Mengapa aku tadi tidak menunggu mbok Pariyem saja,” berkata Ratri dalam hati sambil sesekali mendongakkan kepalanya ke arah barat, “Tapi mbok Pariyem pergi dari pagi dan belum kembali, sedangkan berita ini sangat penting bagi Raden Mas Harya Surengpati.”
Teringat akan Raden Surengpati, tiba-tiba saja wajah Ratri menjadi cerah. Sebuah senyum manis tersungging di bibirnya yang merah menawan. Gadis putri satu-satunya Ki Gede itu sedang beranjak dewasa bagaikan bunga yang sedang mekar-mekarnya. Mengalami masa-masa remaja yang ingin selalu dipuja dan dimanja, dan agaknya Raden Surengpati telah paham akan hal itu. Pengalaman panjangnya bergaul dengan perempuan telah membuat Ratri menjadi mabuk kepayang.
Tiba-tiba Ratri yang sedang termenung itu mendengar langkah-langkah mendekat dari arah barat. Dengan segera dia berpaling sambil bangkit dari duduknya.
“Raden…” desis Ratri dengan suara yang riang penuh kegembiraan begitu mengetahui siapa yang datang.
Yang datang itu memang Raden Surengpati. Sejenak langkahnya tertegun. Dia tidak melihat kawan Ratri yang biasanya selalu setia menemani.
“Engkau sendiri, Ratri?” bertanya Raden Surengpati kemudian dengan pandangan nanar merayapi sekujur tubuh Ratri.
“Ya, Raden,” jawab Ratri sambil menundukkan wajahnya. Jauh di lubuk hatinya dia telah menyesali ketergesa-gesaannya untuk datang ke tempat itu tanpa mbok Pariyem.
“Nah, berita apakah yang engkau bawa kali ini, Ratri?” bertanya Raden Surengpati kemudian sambil berjalan mendekat.
Sejenak Ratri mengangkat wajahnya. Ketika sepasang matanya memandang ke wajah Raden Surengpati, tiba-tiba saja dadanya berdesir tajam. Wajah itu tidak menampakkan sebagaimana biasanya yang ramah dan lembut. Wajah itu tampak mengerikan, merah membara dengan sepasang mata yang liar menelusuri lekuk-lekuk sekujur tubuhnya.
Dengan segera Ratri menundukkan wajahnya kembali. Sambil berusaha menguasai degup jantungnya yang melonjak-lonjak, dia menjawab pertanyaan Raden Surengpati dengan suara bergetar, “Raden, tadi pagi ayah telah mengadakan pertemuan dengan para bebahu perdikan Matesih.”
“O,” desis Raden Surengpati sambil menarik nafas panjang. Darah di sekujur tubuhnya telah mendidih. Dengan langkah satu-satu, orang yang mengaku trah Sekar Seda Lepen itu berjalan semakin dekat.
“Apa yang mereka bicarakan, Ratri?” terdengar suara Raden Surengpati berbisik di dekat telinganya. Begitu dekatnya sehingga Ratri dengan jelas dapat mendengar desah nafasnya yang memburu.
Seketika gemetar sekujur tubuh putri Matesih itu. Berbagai dugaan muncul dalam benaknya. Ada perasaan takut yang menyergap hatinya begitu menyadari apapun bisa terjadi selagi mereka hanya berdua saja di tempat yang sepi itu.
Menyadari bahaya yang setiap saat dapat saja menerkamnya, Ratri segera berusaha menghindar dari tempat itu. Katanya kemudian sambil melangkah surut, “Maaf Raden, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Setiap saat ayah akan memerlukan aku. Aku harus segera kembali ke bilikku.”
“Tidak Ratri,” tiba-tiba terdengar suara Raden Surengpati itu mirip lolong seekor serigala lapar di telinga Ratri, “Akulah yang sekarang memerlukanmu disini. Tidak ada seorang pun yang akan menggangu. Percayalah, aku tidak akan menyakitimu, justru aku akan membahagiakanmu dan sekaligus memberikan sebuah pengalaman yang belum pernah engkau rasakan seumur hidup,” Raden Surengpati berhenti sebentar untuk sedikit meredakan dadanya yang seakan-akan mau meledak. Lanjutnya kemudian, “Inilah kesempatan bagiku untuk membuat Ki Gede menyerah dan menuruti segala kemauanku.”
Bersambung ke jilid 04
(http://tamanbacaanmbahman.blogspot.co.id/)




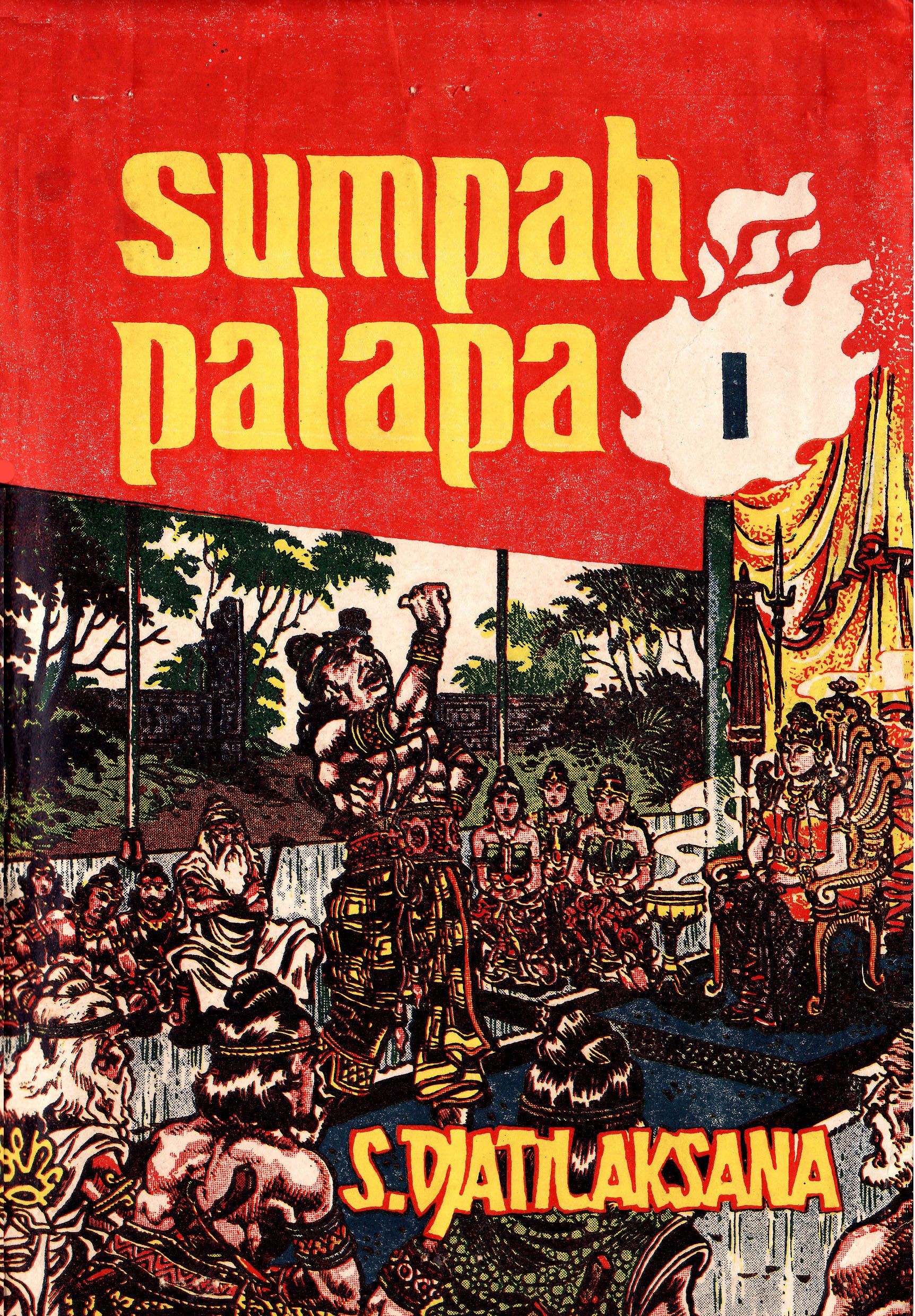

















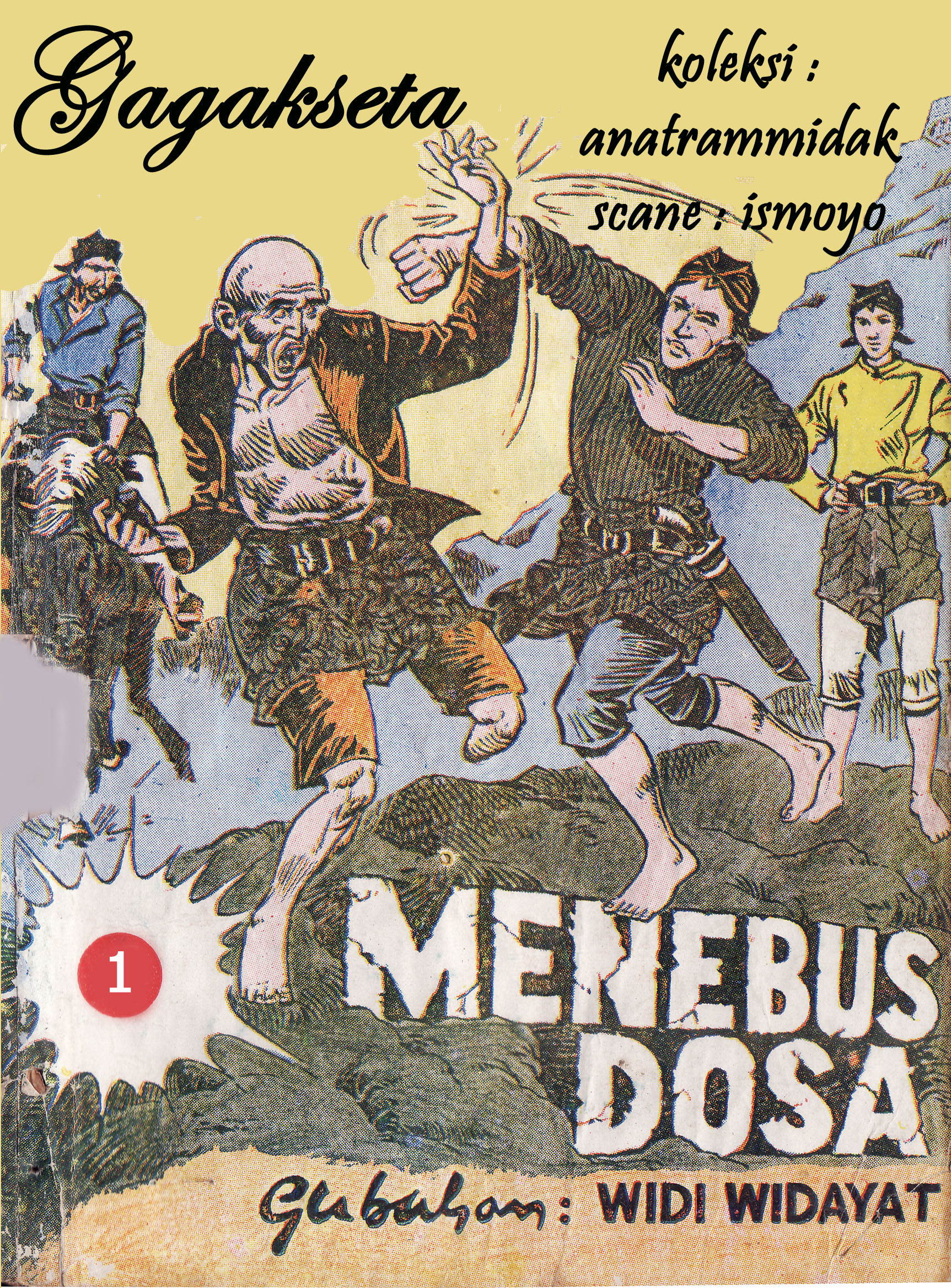


Nyuwun duka dangu mboten sowan,..cantrik samy sowan malih ki….